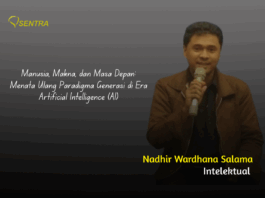Oleh :
Bachtiar S. Malawat (Founder Forum Insan Cendikia Maluku Utara)
Kawan-kawan, Setiap tahun bangsa Indonesia merayakan tanggal 17 Agustus dengan gegap gempita. Jalan-jalan dihiasi bendera merah putih, lomba rakyat digelar di setiap sudut desa, dan suara pidato para pejabat menggema dengan penuh semangat. Anak-anak muda yang belum pernah merasakan pahit getir penjajahan pun ikut berbaris dengan bangga di lapangan upacara. Semua seolah-olah menegaskan bahwa Indonesia sudah merdeka. Tetapi, perlu kita sedikit merenung degan sebuah pertanyaan sederhana apakah benar kita sudah merdeka? Pertanyaan itu tak pernah selesai, karena kemerdekaan ternyata tidak cukup hanya diikrarkan pada 1945, tidak cukup hanya diabadikan dalam dokumen proklamasi, dan tidak cukup hanya dikenang setiap tahun lewat seremonial.
Kemerdekaan sejati seharusnya berarti terbebas dari segala bentuk penindasan, baik oleh bangsa asing maupun oleh bangsa sendiri. Sederhananya yang lapar bisa makan, kemerdekaan bukan hanya tentang pengusiran penjajah dari bumi Nusantara, tetapi juga tentang tegaknya kedaulatan rakyat, berdirinya kemandirian bangsa, serta terjaminnya keadilan sosial. Namun jika kita mau jujur, banyak fakta di negeri ini yang justru memperlihatkan betapa kata “merdeka” masih penuh tanda tanya. Kita merayakan kemerdekaan dengan pesta, tetapi di sudut-sudut negeri, ada petani yang gagal panen karena harga jatuh, ada nelayan yang perahunya kalah oleh kapal-kapal besar yang mengeruk laut dengan alat modern, ada buruh yang dipaksa bertahan hidup dengan upah murah, dan ada anak-anak yang harus berhenti sekolah karena biaya tak mampu ditanggung keluarga. Jika kondisi seperti ini masih terjadi, pantaskah kita menyebut diri telah merdeka. Penulis mengangap ini seperti mimpi di siang bolong.
Sejak awal, para pendiri bangsa merumuskan kemerdekaan Indonesia bukan hanya untuk mengganti bendera, tetapi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembukaan UUD 1945 jelas menegaskan tujuan itu, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Namun delapan dekade setelah proklamasi, keadilan sosial itu masih jauh panggang dari api. Kesenjangan ekonomi semakin lebar dan lebar sekali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat koefisien gini ukuran ketimpangan masih bertahan di angka 0,388. Artinya, jurang antara si kaya dan si miskin semakin menganga. Segelintir orang menguasai sumber daya alam, sementara mayoritas rakyat hanya menerima sisa-sisa. Indonesia yang kaya raya dengan tambang emas, nikel, minyak, gas, dan hutan ternyata belum mampu membuat rakyatnya sejahtera. Ironisnya, kekayaan itu justru sering dikuasai oleh perusahaan besar, baik asing maupun lokal, yang berkolaborasi dengan elit politik. Maka tidak berlebihan jika penilis menyebut bahwa kita telah merdeka secara politik, tetapi masih terjajah secara ekonomi.
Dalam dunia politik, demokrasi yang dipuja-puja sebagai simbol kedaulatan rakyat sering kali terjebak dalam praktik transaksional. Pemilu yang semestinya menjadi ruang rakyat menentukan arah bangsa berubah menjadi arena jual beli suara. Uang lebih berkuasa daripada gagasan, popularitas lebih penting daripada integritas, dan kepentingan segelintir elit lebih diutamakan daripada suara rakyat. Apakah ini wajah demokrasi yang dicita-citakan, atau bagaimana. Bukankah dalam praktik seperti ini rakyat justru kembali dijajah, kali ini oleh bangsanya sendiri, Soekarno pernah berujar, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Kalimat itu kini terasa nyata.