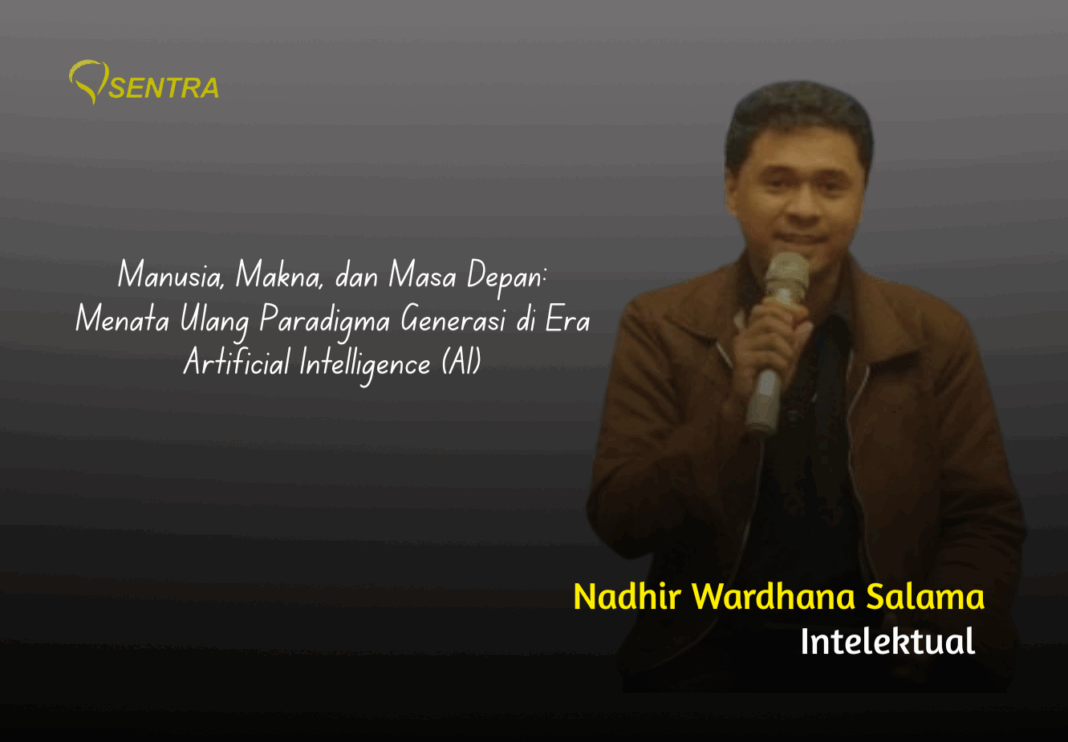Oleh:
Nadhir Wardhana Salama (Beyond Health Indonesia/Research and Policy Center ILUNI FKM UI
Di setiap simpang sejarah, manusia selalu dihadapkan pada pertanyaan yang sama: siapa kita, ke mana kita menuju, dan apa arti keberadaan kita? Pertanyaan ini kembali mengemuka di abad ke-21, ketika peradaban memasuki era Artificial Intelligence (AI) sebuah era di mana kemampuan berpikir, yang dulu menjadi monopoli manusia, kini mulai dibagi dengan entitas buatan. Seperti halnya kapal yang meninggalkan dermaga menuju samudra tak dikenal, kita melangkah dengan rasa kagum sekaligus waspada.
Peradaban manusia selalu ditandai oleh titik balik teknologi mulai dari penemuan roda, mesin uap, listrik, hingga internet. Kini, kita menghadapi babak baru: Artificial Intelligence (AI), sebuah entitas non-biologis yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara otonom. Jika revolusi industri memindahkan otot manusia ke mesin, maka revolusi AI berpotensi memindahkan sebagian fungsi otak manusia ke algoritma. Pertanyaannya, bagaimana manusia tetap relevan, dan apa makna keberadaan kita di tengah sistem yang semakin otomatis?
Secara teknokratis, AI adalah instrumen percepatan efisiensi. Ia dapat mengolah data dalam skala yang mustahil dikerjakan manusia dalam waktu singkat. Dari sektor keuangan hingga kesehatan, AI membentuk model prediksi, meminimalkan kesalahan, dan mengoptimalkan sumber daya. Namun di balik kecanggihan itu, ada paradoks: ketika mesin dapat mengambil alih fungsi berpikir, apa yang tersisa bagi manusia selain menjadi operator atau penonton proses yang telah diprogram?
Paradigma generasi harus bergeser dari sekadar “mencari pekerjaan” menjadi “menciptakan makna”. Pada era pra-AI, manusia dihargai karena kemampuan fisik dan kognitifnya. Kini, nilai manusia akan terletak pada kapasitasnya untuk menghadirkan perspektif, etika, dan kebijaksanaan hal-hal yang belum dapat direplikasi oleh algoritma secara otentik. Kompetensi teknis memang penting, tetapi tanpa landasan nilai, kita hanya akan menjadi perpanjangan tangan dari logika mesin.
Secara filosofis, era AI memaksa kita meninjau ulang relasi antara manusia dan teknologi. AI bukan sekadar alat, tetapi cermin yang memantulkan bias, niat, dan visi penciptanya. Jika AI digunakan untuk memaksimalkan keuntungan tanpa memedulikan keadilan, maka ketimpangan sosial akan melebar. Jika AI diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi publik, maka ia menjadi instrumen kemajuan kolektif. Di sinilah peran generasi kini menentukan arah moral dari teknologi yang mereka warisi dan kembangkan.
Masa depan bukanlah tentang manusia yang kalah atau menang dari mesin, melainkan tentang koeksistensi yang cerdas. Generasi yang akan bertahan adalah mereka yang memadukan kecerdasan digital dengan kecerdasan emosional dan moral. Pendidikan harus bertransformasi dari sistem yang menghafal fakta menjadi sistem yang mengasah critical thinking, problem solving, dan literasi etis. Pemerintah dan sektor swasta perlu membangun kerangka regulasi yang bukan hanya mengatur, tetapi juga membimbing perkembangan AI agar selaras dengan kepentingan manusia jangka panjang.