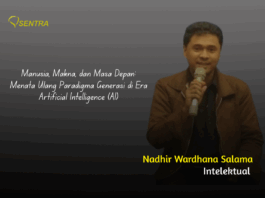Kondisi serupa juga bisa kita temui di Halmahera Selatan. Desa-desa di Bacan Barat Utara misalnya, kaya dengan hutan dan lahan pertanian, tetapi akses jalan, pendidikan, dan kesehatan masih jauh dari memadai. Anak-anak harus berjalan kaki berjam-jam untuk sampai ke sekolah, sementara guru dan fasilitas sering tidak mencukupi. Orang tua mereka berjuang mengolah kebun cengkeh atau pala, tetapi harga di pasar ditentukan oleh tengkulak. Rantai perdagangan membuat mereka selalu berada pada posisi paling lemah. Mereka yang bekerja keras memanen tidak pernah menikmati harga yang layak, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati oleh para pedagang besar di kota. Bukankah ini bentuk penjajahan gaya baru yang membuat rakyat desa tetap berada dalam lingkaran kemiskinan.
Kita juga bisa menengok ke Halmahera Timur, di mana perusahaan tambang emas dan nikel beroperasi di dekat pemukiman masyarakat adat. Hutan yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan, tempat berburu, dan tempat mencari kayu, perlahan-lahan hilang. Sungai yang dulunya jernih kini berubah keruh. Masyarakat adat kehilangan ruang hidup, dan generasi mudanya terpaksa bekerja sebagai buruh kasar di perusahaan tambang yang justru merampas tanah mereka. Tan Malaka pernah menulis bahwa penjajahan tidak selalu datang dengan kapal perang dan senjata, melainkan bisa datang lewat modal dan perjanjian-perjanjian ekonomi yang merugikan rakyat. Kalimat itu hari ini terasa nyata di Maluku Utara.
Tidak hanya di sektor ekonomi dan lingkungan, ketidakmerdekaan juga tampak jelas dalam wajah politik lokal. Pilkada dan Pilkades di Maluku Utara sering kali berlangsung panas, bukan karena perdebatan gagasan, tetapi karena politik uang dan patronase. Banyak masyarakat yang akhirnya terbelah karena memilih berdasarkan siapa yang memberi lebih banyak uang atau janji bantuan. Demokrasi yang mestinya melahirkan kepemimpinan rakyat justru terjebak dalam lingkaran transaksional. Hasilnya, yang terpilih bukanlah pemimpin visioner yang mampu membawa rakyat pada kemandirian, melainkan figur yang sibuk mengembalikan modal politik. Bukankah ini juga tanda bahwa kemerdekaan politik kita masih sebatas kulit? Rakyat hanya merdeka memilih, tetapi tidak merdeka menentukan nasibnya sendiri. Ngeriii.
Di sisi lain, pendidikan di Maluku Utara masih menyedihkan. Data BPS 2024 menunjukkan rata-rata lama sekolah di provinsi ini masih sekitar 9 tahun, atau setara SMP. Artinya banyak anak yang belum merasakan bangku SMA, apalagi perguruan tinggi. Padahal kemerdekaan berarti juga memberi kesempatan yang sama bagi anak bangsa untuk menempuh pendidikan. Jika anak-anak di Ternate bisa dengan mudah mengakses sekolah menengah dan universitas, mengapa anak-anak di Obi, Loloda, atau Maba masih harus menyeberangi laut dan menempuh perjalanan jauh hanya untuk belajar? Jika ketimpangan ini terus terjadi, maka kemerdekaan pendidikan itu Omong kosong.
Kesehatan juga memperlihatkan wajah kemerdekaan yang timpang. Di kota besar seperti Ternate, rumah sakit relatif tersedia, meski dengan fasilitas terbatas. Tetapi di desa-desa kepulauan, akses kesehatan sering kali hanya berupa puskesmas pembantu dengan tenaga minim. Masyarakat yang sakit parah harus menunggu kapal untuk dirujuk ke kota, dan banyak yang akhirnya meninggal di perjalanan. Apakah ini wujud bangsa yang merdeka? Bagaimana mungkin kita berteriak merdeka, sementara rakyat di kepulauan masih sulit mendapatkan hak dasar untuk hidup sehat.